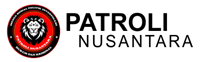Oleh Jacob Ereste
Opini | patrolinusantara.press – Pencitraan yang dilakukan oleh pejabat publik itu awal dari kemunafikan. Sebab apapun yang dilakukan pejabat publik tak terlalu penting untuk diketahui secara meluas dengan cara melakukan pencitraan itu. Sebab apa yang harus dilakukan itu adalah kewajiban dan tanggung jawab yang sudah harus dan wajib dilakukan, tanpa perlu mendapat pujian.
Pencitraan itu adalah hasrat untuk dipuji dari apa yang dilakukan. Padahal, apa yang dilakukan pejabat publik itu yang terpenting adalah kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat atau orang banyak.
Jadi pencitraan itu sekedar hasrat untuk dipuji dan merebut simpati dengan cara mencari perhatian agar memperoleh decak dan kekaguman dari orang lain sehingga bisa dianggap hebat. Artinya, apa yang dilakukan itu tidak lebih penting dari sensasi yang ingin diperoleh supaya bisa dianggap sebagai pahlawan yang berhak untuk membanggakan diri. Maka itu, ketika pejabat publik berprilaku berlebihan — seperti harus nyemplung ke dalam parit atau got — itu terkesan menjadi sangat konyol dan kampungan. Artinya, kemampuan untuk memahami dan menganalisa parit atau got itu berada diluar kemampuan daya nalar maupun pengetahuan, maka perilaku serupa itu jadi dianggap wajar oleh yang bersangkutan.
Saat menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024, banyak orang yang pasang aksi mencari perhatian agar dapat memperoleh tempat, baik dalam proses Pilpres dan Pileg maupun kelak sesudah kalkulasi kemenangan akan dibagi-bagikan sebagai jatah atau upah atas jasa yang telah dilakukan saat merebut kemenangan. Itulah sebabnya cara memenangkan Pilpres maupun Pileg lebih sering (dominan) dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
Yang tak sedap ialah melakukannya dengan tipu daya terhadap rakyat (pemilih) dengan cara mengumbar janji dan memberi sembako (sembilan bahan pokok, yang cuma diwakili oleh 5 kg beras dan beberapa bungkus mei instant saja) yang disertai nada tekanan (setengah ancaman) bila nanti harus memilih dirinya atau orang yang dijagokannya agar bisa menang dalam Pilpres atau Pileg. Sedangkan janji yang sudah biasa diumbar itu menjadi hal yang dianggap biasa yang diingkari nantinya. Misalnya janji membangun sarana jalan hingga gedung pertemuan atau tempat ibadah, tak terlalu penting bisa diwujudkan atau tidak, persis seperti dana untuk itu semua nanti entah dari asal usulnya.
Biasanya juga, janji muluk serupa ini memang cuma janji belaka. Sebab setelah menang, toh lebih banyak urusan lain yang harus lebih diutamakan setidaknya untuk memperkuat diri dari posisi secara finansial maupun dalam struktur kekuasaan yang akan terus jadi pertikaian dan rebutan.
Masalah ingkar janji dari mereka yang sudah duduk enak di singgasana kekuasaan itu juga tidak sedikit yang dialami oleh para aktivis atau mereka yang sering disebut sebagai kaum pergerakan saat berada dalam satu garis perjuangan yang memang sejak awal sudah berpamrih mendapatkan jabatan.
Begitulah realitas sosial dan realitas politik yang tidak bisa diramalkan sebelumnya seperti cuaca ekstrim semacam hujan dan panas. Karena siklusnya memang tidak konsisten yang cermin dalam etika, moral dan akhlak yang semestinya sudah terbingkai dalam keimanan setiap orang yang patut disebut beragama dengan baik dan benar. Maka itu, dalam aktivitas politik, jelas sekali jika etik profetik — tuntunan dan ajaran para Nabi yang dikirim Tuhan dari langit itu — patut menjadi sandaran dan pegangan agar tak sampai terjerembab dan nyungsep ke dalam jurang yang gelap dan mengerikan. Jika tidak, toh resiko memang kelak akan ditanggung sendiri. Yang celaka memang, karma dan azab itu bisa mendera juga anak, istri dan cucu.
Nagrak, 16 Mei 2023